‘Boncos’ ongkos pilkada karena praktik politik menyimpang
Membengkaknya anggaran pilkada dinilai bukan karena prosedur demokratis, melainkan praktik politik yang memang menyimpang.

Wacana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ingin mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai berpotensi melemahkan kedaulatan rakyat dan mendorong kemunduran demokrasi.
Table Of Content
Hal itu dikemukakan oleh Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia.
Menurut Alfath, pencabutan hak pilih langsung dari warga hanya akan memperkuat elite politik dan menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan.
“Dengan pilkada langsung saja aspirasi masyarakat kerap diabaikan, apalagi jika pilkada diserahkan ke DPRD. Ini hanya akan mengabaikan masyarakat dari sistem sosial-politik kita,” ujar Alfath, Selasa (20/1/2026).
Menurutnya, meskipun DPRD dipilih melalui pemilu, dalam praktiknya wakil rakyat tidak sepenuhnya lepas dari kepentingan elite partai.
“Faktanya, DPRD tidak mampu melepaskan diri dari kepentingan elite partai mereka, bukan semata kepentingan rakyat. Kebijakan ini hanya akan mengalienasi rakyat dan memperkuat posisi elite,” tegasnya.
Pembengkakan anggaran tanda praktik politik menyimpang
Terkait alasan mahalnya biaya pilkada sehingga harus dikembalikan melalui pemilihan di tingkat DPRD, Alfath menilai pembengkakan anggaran bukan berasal dari prosedur demokratis, melainkan dari praktik politik yang menyimpang.
“Seorang kandidat harus mengeluarkan biaya besar sejak mendapatkan kendaraan politik, biaya kampanye, logistik, hingga politik uang. Ditambah lagi jika terjadi pemungutan suara ulang dan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK),” jelasnya.
Ia menyebut ada persoalan mendasar dalam demokrasi elektoral Indonesia yang bersumber pada tiga masalah utama, yakni kapasitas politisi yang buruk, rendahnya literasi politik masyarakat, dan politik programatik yang belum menjadi arus utama.
Tiga masalah utama itu menyebabkan demokrasi elektoral di Indonesia menemui titik kontroversial.
Alfath menilai praktik adanya mahar politik dan politik uang memiliki kontribusi signifikan terhadap tingginya ongkos pilkada.
“Mahar politik di level pencalonan dan politik uang saat kampanye menciptakan cost spiral. Ongkos pilkada membengkak bukan karena prosedurnya, tapi karena praktik informal yang ditoleransi dan sulit ditegakkan hukumnya,” ujarnya.
Ia bahkan mengkritik laporan dana kampanye yang dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Sebab, dokumen dana kampanye itu lebih tepat disebut wajar tanpa pemeriksaan, bukan wajar tanpa pengecualian.
Penghapusan pilkada langsung bukan jawaban
Oleh karena itu, Alfath menilai penghapusan pilkada langsung bukanlah jawaban. Sebab, sumber masalahnya bukan pada pilkada langsung, tetapi pada political financing.
“Menghapus pilkada langsung itu hanya mengobati gejala, bukan penyakit”, tegasnya.
Ia mendorong pembenahan menyeluruh pada pendanaan politik, mulai dari transparansi dana kampanye, reformasi rekrutmen kandidat di internal partai, hingga penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang.
Alfath mengatakan, perlu pembukaan ruang peningkatan pendanaan negara untuk partai politik, dengan syarat akuntabilitas publik diperkuat.
“Jika negara meningkatkan pembiayaan parpol, maka akuntabilitas sosial dan publik partai juga harus ditingkatkan. Dana itu harus jelas peruntukannya, misalnya untuk pendidikan politik dan kaderisasi,” ujarnya.
Baca juga: Pemilu tidak langsung bukan berarti biayanya lebih kecil
Jika kepala daerah dipilih DPRD, Alfath mengingatkan akan terjadinya pergeseran akuntabilitas.
Pasalnya, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada warga, melainkan kepada elite partai dan fraksi. Mereka diprediksi akan lebih memikirkan tentang elite ketimbang masyarakat.
Hal ini berpotensi meningkatkan risiko elite capture dan transaksi kebijakan pasca-pilkada. Alfath menekankan pentingnya peran masyarakat sipil untuk mencegah kemunduran demokrasi dengan adanya rencana pilkada lewat DPRD.
“Masyarakat sipil perlu menggeser debat dari soal mahalnya demokrasi ke pertanyaan: siapa yang diuntungkan dari perubahan ini”, tuturnya.
Tiga agenda reformasi mendesak
Kendati pilkada langsung harus tetap dipertahankan, Alfath menekankan tiga agenda reformasi mendesak untuk dilaksanakan.
Jika tiga agenda reformasi ini tidak dilaksanakan, maka pilkada langsung tetap akan menguras kantong calon kepala daerah, menyebabkan siklus keboncosan berulang.
Pertama, pembatasan dan audit ketat dana kampanye secara real-time.
Kedua, reformasi tata kelola dan rekrutmen kandidat partai serta ketiga, penegakan hukum politik uang yang tidak tebang pilih.
“Tanpa reformasi ketiga hal itu, pilkada langsung akan terus mahal dan rapuh dari sisi legitimasi demokratis,” pungkasnya.








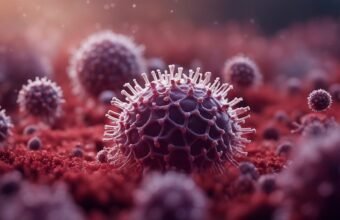


No Comment! Be the first one.