Pemilu tidak langsung bukan berarti biayanya lebih kecil
Pemilu tidak langsung kembali dibicarakan pemerintah dengan dalih menekan ongkos politik yang gila-gilaan, tapi bagaimana risikonya?

Wacana pemilu tidak langsung atau pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menguat dengan dalih efisiensi dan pengurangan biaya politik, termasuk politik uang untuk para pendukung yang masih merajalela dalam setiap pilkada.
Table Of Content
Namun, di balik argumen tersebut, tersimpan persoalan yang kerap luput dibahas, yakni politik uang tidak serta merta hilang ketika rakyat tak lagi memilih secara langsung.
Pakar politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Tunjung Sulaksono menjelaskan perubahan mekanisme pilkada akan mengubah arena pertarungan politik lokal secara signifikan.
Kompetisi, kata dia, tidak lagi berlangsung di ruang publik yang luas, melainkan bergeser ke ruang tertutup yang melibatkan aktor terbatas.
“Arena kompetisi berpindah dari adu program dan rekam jejak di hadapan jutaan pemilih, menjadi negosiasi di hadapan puluhan anggota DPRD. Kampanye pun berubah dari kampanye kepada rakyat menjadi kampanye kepada fraksi-fraksi,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (13/6/2026).
Persempit ruang representasi politik
Tak hanya itu, Tunjung menyoroti dampak sistem pemilu tidak langsung terhadap representasi politik.
Bisa dibilang kandidat independen tidak akan memiliki ruang gerak.
Dalam banyak kasus, pemilihan melalui DPRD justru berpotensi mempersempit ruang representasi dan menutup peluang kandidat independen maupun figur yang memiliki dukungan kuat di tingkat akar rumput.
“Keputusan politik cenderung mengerucut pada elit partai. Kandidat independen praktis tidak memiliki ruang, dan figur yang populer di masyarakat bisa kalah hanya karena tidak mendapat restu elit,” kata Tunjung.
Lebih lanjut, ia menilai penghapusan pemilihan langsung berpotensi menurunkan partisipasi politik dan kepercayaan publik. Ketika masyarakat kehilangan hak memilih secara langsung, keterlibatan warga dalam politik lokal juga berisiko melemah.
Ada tiga risiko besar
Dalam jangka panjang, Tunjung mengidentifikasi setidaknya tiga risiko besar jika pemimpin tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat.
“Pertama, oligarki lokal akan semakin menguat karena kepemimpinan daerah ditentukan oleh jaringan elit dan kekuatan modal. Kedua, akuntabilitas kepala daerah melemah karena orientasinya lebih tertuju pada DPRD daripada warga. Ketiga, politik uang tidak hilang, melainkan hanya berpindah arena, dari membeli suara rakyat menjadi membeli suara elit, yang justru lebih tertutup dan sulit diawasi,” paparnya.
Pemilu tidak langsung masih dibenarkan
Dijelaskannya, secara konstitusional, mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD memang masih dapat dibenarkan.
Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, tanpa merinci apakah mekanismenya harus dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
Namun, Tunjung mengingatkan bahwa kualitas demokrasi tidak semata-mata diukur dari aspek legal-formal.
“Secara teori, pemilihan oleh DPRD masih bisa disebut sebagai bentuk kedaulatan rakyat karena DPRD merupakan hasil pemilu. Namun, pertanyaan krusialnya adalah apakah rantai kedaulatan itu masih utuh, atau justru terputus oleh transaksi elit politik,” ujarnya.
Menanggapi wacana tersebut, Tunjung menegaskan bahwa solusi utama seharusnya tidak dimulai dengan menghapus mekanisme pemilihan langsung, melainkan dengan membenahi persoalan hulu dalam sistem politik elektoral, seperti rekrutmen kader partai, pendanaan politik, dan pengawasan pemilu.








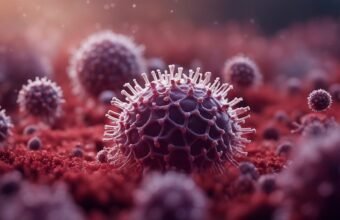


[…] Baca juga: Pemilu tidak langsung bukan berarti biayanya lebih kecil […]