Fenomena ambivalensi demokrasi Indonesia: Mengapa gen Z pilih sosok ‘strongman’?
Ambivalensi politik muncul di Indonesia. Hal itu terlihat dalam Pemilu 2024 dimana pasangan Prabowo-Gibran berhasil menang. Gen Z dianggap memilih sosok ‘strongman’ demi ketertiban.

Di tengah penerimaan luas terhadap pemilu dan prosedur demokrasi, sebagian generasi Z justru menunjukkan kecenderungan memilih sosok pemimpin kuat atau strongman, tidak terkecuali figur berlatar belakang militer.
Table Of Content
Fenomena ini, menurut Guru Besar Hukum Kelembagaan Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Zainal Arifin Mochtar, merupakan ambivalensi demokrasi.
Artinya, generasi muda tetap mengafirmasi demokrasi, tetapi bersedia mengorbankan unsur-unsur penting, seperti pengawasan, pembatasan kekuasaan, demi janji stabilitas, ketertiban, dan kepemimpinan yang dianggap tegas.
“Burhanuddin Muhtadi (Direktur Lembaga Survey Indikator Politik Indonesia) mencatat bahwa dibalik kemenangan Prabowo dalam Pemilu 2024, juga ada sumbangsih publik pemilih, khususnya generasi Z yang bergerak semakin ‘konservatif’,” ujar Zainal atau yang akrab disapa Uceng tersebut.
Uceng menjelaskan hal tersebut dalam pidato pengukuhan guru besar berjudul Konservatisme yang Menguat dan Independensi Lembaga Negara yang Melemah: Mencari Relasi dan Mendedah Jalan Perbaikan di Balairung UGM, Kamis (15/1/2026).
Dia menyebut, pergerakan itu bukan karena nostalgia dan kangen pada rezim orde baru.
Masyarakat, khususnya pemilih muda, memang tetap mendukung pelaksanaan pemilu secara prosedural.
Namun, di saat yang sama, mereka menunjukkan penerimaan yang lebih tinggi terhadap pemimpin yang kuat serta peran militer dalam pemerintahan.
“Di Film ‘Dirty Vote’, telah dijelaskan juga faktor-faktor lain dalam konteks kooptasi personal dan dapat dipakai untuk menjelaskan dasar mengapa Prabowo dapat memenangkan Pemilu 2024. Jika diakumulasikan, seakan menunjukkan ambivalensi demokrasi di Indonesia,” bebernya panjang.
Korbankan substansi demokrasi demi ketertiban
Menurut pendapat Uceng, hal yang paling mengkhawatirkan dari tren ini adalah kesediaan generasi muda untuk melepaskan nilai-nilai liberal.
Ia memaparkan bahwa kelompok ini cenderung bersedia mengorbankan unsur-unsur demokrasi yang krusial, seperti:
- Keterbukaan informasi dan transparansi.
- Mekanisme pengawasan (oversight).
- Pembatasan kekuasaan dan supremasi sipil.
Dukungan terhadap sosok strongman ini sering kali dibalut dengan narasi konservatisme ketertiban.
Arus ini muncul karena adanya kelelahan publik terhadap konflik politik dan birokrasi yang dianggap lamban, sehingga gagasan mengenai penertiban demokrasi melalui kontrol negara yang sentralistik kembali mendapatkan legitimasi moral.
Celah bagi pemimpin illiberal
Pergeseran sikap Gen Z ini dinilai menjadi celah lebar bagi munculnya pemimpin yang bersifat illiberal, kata Uceng.
Ketika publik memberikan mandat kepada sosok pemimpin kuat dengan mengabaikan prinsip checks and balances, lembaga-lembaga negara independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), menjadi pihak yang paling rentan dikuasai atau dilemahkan.
Hal ini memang sudah terjadi di Indonesia.
Dikatakannya, kegaduhan politik elektoral, maraknya disinformasi, dan kekecewaan publik terhadap elite partai membuka ruang bagi gagasan restoratif.
Namun, yang berkembang adalah gagasan demokrasi perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan ketidakstabilan.
Dalam atmosfer seperti itu, lembaga independen yang bersifat pengawas sering kali dipandang sebagai hambatan bagi kecepatan pemerintah dan dianggap tidak akuntabel secara politik.
“Secara garis besar, menguatnya konservatisme di Indonesia bukan sekadar reaksi ideologis terhadap liberalisme, tetapi juga strategi politik untuk mengembalikan struktur kekuasaan negara ke orbit lama yang lebih hierarkis dan terpusat,” tambahnya.
Itu bekerja melalui mekanisme legal-formal yang sah, tetapi menghasilkan efek politik yang bersifat erosif terhadap independensi kelembagaan.
Penguatan demokrasi dilakukan multidisipliner
Dalam kondisi global yang memang mengarah ke konservatisme, Uceng menegaskan bahwa kondisi ini bukan berarti tanpa jalan keluar.
Ia menolak gagasan bahwa penguatan demokrasi dapat diselesaikan hanya dengan perbaikan aturan atau desain kelembagaan semata.
Menurutnya, pendekatan multidisipliner yang mencakup analisisi ekonomi-politik, penguatan masyarakat sipil, serta dukungan komunitas internasional menjadi kunci untuk menciptakan arus balik demokrasi.
“Independensi lembaga bukan kondisi final, melainkan proses yang terus dinegosiasikan. Tanpa dukungan publik dan masyarakat sipil yang kuat, lembaga-lembaga ini akan selalu rapuh,” ujarnya.
Menutup pidatonya, Zainal menekankan bahwa hidup dan matinya lembaga negara independen adalah cermin kedewasaan demokrasi suatu bangsa.
Ia menyebut, ketika lembaga-lembaga pengawas dilemahkan, yang sesungguhnya tergerus bukan hanya institusi, melainkan kepercayaan publik terhadap hukum dan negara.
“Yang perlahan mati bukan sekadar lembaga, tetapi idealisme demokrasi yang pernah kita perjuangkan bersama,” pungkasnya.









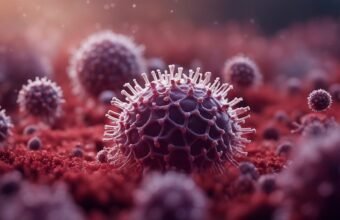

No Comment! Be the first one.