Selamat datang refeudalisasi ruang publik
Refeudalisasi ruang publik terjadi saat politik partai dan media massa melakukan manipulasi. Yakni saat masyarakat yang rasional dan kritis ditransformasikan menjadi masyarakat massa dan dimanipulasi...

Penangkapan sejumlah aktivis sosial politik, teror dan disertasi kekerasan pada sejumlah pihak yang mengkritik penguasa serta pemberlakuan KUHP, KUHAP adalah bagian dari upaya pelemahan demokrasi.
Table Of Content
Hal tersebut berlawanan dengan spirit pembatasan kekuasaan dan kebebasan berpendapat serta berekspresi. Pemerintah secara resmi mensponsori kondisi ini. Bagi publik hal tersebut adalah upaya pelemahan akal sehat.
Jika melihat fenomena ini, sejatinya hal tersebut dapat dilihat dari kacamata yang menarik.
Sosiolog Jerman Juergen Habermas melahirkan konsep yang sangat populer yakni ruang publik (public sphere) yang merujuk pada ‘ruang’ komunikasi rasional yang bertujuan untuk kebaikan bersama yang bebas dari pembatasan dan pengecualian.
Pada publikasinya berjudul The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964) Habermas menyebut bahwa ruang publik adalah wilayah kehidupan sosial dimana opini publik dapat dibentuk.
Opini publik dalam hal ini mengacu pada kritik dan kontrol yang dilakukan publik. Tidak hanya itu, pada ruang ini, akses semua warga negara dijamin sehingga memungkinkan diskusi dilakukan dengan tak terbatas.
Warga mendapatkan garansi untuk berkumpul dan kebebasan mengekspresikan serta mempublikasikan pendapat mereka berkaitan dengan kepentingan umum.
Habermas menekankan bahwa otoritas negara dapat dikatakan sebagai pelaksana ruang politik namun mereka bukankah bagian dari ruang publik. Tugas negara adalah menjaga kesejahteraan semua warga terutama atas kebutuhan mereka pada ruang publik ini.
Ruang publik, tambah Habermas, dapat terwujud jika kontrol politik tunduk pada tuntutan demokrasi, yakni utamanya pada aspek bahwa informasi harus dapat diakses oleh publik.
Untuk memfasilitasi semua ini, diperlukan media untuk ruang publik yakni media massa. Pada aspek ini, media massa memegang peran yang penting.
Selain konsep yang sangat terkenal itu, Habermas juga menyoroti kondisi yang bertolak belakang dengan bebasnya ruang publik. Kondisi itu dinamakan dengan refeudalisasi (refeudalization) ruang publik.
Partai politik dan media massa melakukan manipulasi
Dalam ulasan menarik yang ditulis oleh Sonia Livingstone dan Peter Lunt disinggung bahwa refeudalisasi ruang publik terjadi saat politik partai dan media massa melakukan manipulasi.
Yakni saat masyarakat yang rasional dan kritis ditransformasikan menjadi masyarakat massa dan dimanipulasi oleh otoritas tertentu. Ruang publik dirusak, salah satunya, dengan perluasan intervensi negara.
Perluasan intervensi negara membuat ruang publik tidak lagi berisi informasi yang beragam dan bebas. Informasi lalu didominasi oleh segelintir orang yakni negara dan pihak-pihak yang terfasilitasi oleh negara atau diuntungkan oleh situasi ini.
Di Indonesia, informasi dari masyarakat justru dilabeli sebagai misinformasi dan sesuatu yang mengada-ada.
Akibatnya, media sebagai ruang publik, yang seharusnya sarat informasi dan diskusi, tidak dapat berkerja secara maksimal karena terkendala prasyarat dasar.
Pertama, akses kepada informasi dibatasi. Kedua, terdapat bias kelas yang sangat terasa karena informasi hanya diproduksi oleh golongan tertentu.
Bahkan, sekarang publik semakin sering mendengar idiom ‘antek asing’ untuk menyebut pihak yang mengkritik pemerintah. Masyarakat diposisikan sebagai musuh sekaligus dicurigai sebagai orang yang ingin menyabotase program negara.
Harapan negara demokrasi sulit tercapai
Pada titik ini, cita-cita negara demokrasi mungkin akan sulit dicapai. Brian McNair pada publikasinya mengulas setidaknya menyebut tiga hal yang menjadi karakteristik rezim demokrasi.
Pertama, konstitusionalitas. Konstitusionalitas merujuk pada kondisi adanya seperangkat prosedur dan aturan yang disepakati dan mengatur pada setidaknya tiga hal yakni pelaksanaan pemilu, pemenang pemilu serta pengkritik atau oposisi.
Kedua, partisipasi publik. Pada mekanisme ini maka proses pengambilan keputusan menjadi proses yang menanti kehadiran publik.
Keterlibatan adalah cara untuk menunjukkan penghargaan kepada keberadaan publik sekaligus untuk menjamin bahwa proses bernegara tidak hanya perlu disaksikan oleh publik namun juga penghargaan pada keterlibatan masyarakat. Dengan demikian transparansi dan legitimasinya terjaga.
Ketiga, rational choice. Aspek ini sangat penting mengingat demokrasi memungkinkan tersedianya pilihan dan kemampuan warga negara untuk menggunakan pilihan itu secara rasional.
Pada masyarakat yang berwawasan dan berpendidikan, situasi ini lebih mudah dibayangkan.
Namun demikian, rational choice tidak dapat hadir tanpa ketercukupan informasi. Akses dan pasokan informasi yang mumpuni, beragam serta bermakna adalah energi yang vital.
Dengan begitu, upaya pelemahan akal sehat publik terjadi melalui berbagai kebijakan termasuk yang termanifestasi melalui regulasi dan wacana.
Hal ini jelas terlihat pada pembahasan revisi UU Penyiaran pada tahun 2024 lalu.
Dalam draft UU Penyiaran itu, masyarakat semakin dipersulit untuk mendapatkan informasi yang bergizi bagi nalar karena penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi dibatasi.
Tidak hanya itu, partisipasi publik juga menjadi hal yang semakin jauh karena limitasi akses terhadap informasi berkedalaman serta penting.
Padahal pada produk investigasi, masyarakat lebih mungkin untuk mengawasi pemerintah termasuk terlibat dalam pembuatan aturan serta proses pemilu.
Pemilu menjadi sangat penting karena inilah mekanisme yang menghasilkan pemimpin dalam periode tertentu.
Tidak hanya itu, RUU ini juga tidak konsisten dalam kaitannya dengan UU lainnya.
Pada bagian larangan konten siaran yang mengantung penghinaan dan pencemaran nama baik, RUU ini ‘cukup nyambung’ dengan UU ITE.
Namun, pada bagian lain yakni pada pasal 51 huruf E berpotensi overlapping dengan UU Pers tahun 1999 soal penyelesaian sengketa jurnalistik yang berada di bawah Dewan Pers.
Intervensi negara sedemikian rupa
Pasal-pasal yang tidak konsisten itu merupakan contoh bahwa intervensi negara difasilitasi sedemikian rupa dengan cara membatasi ruang dan alat produksi informasi.
’Pilihan-pilihan’ akan informasi yang terbatas ini bahkan berkorelasi dengan kondisi bisnis media yang tidak mudah diisi oleh pemain baru yang tak bermodal besar.
Belum selesai dengan kontroversi tersebut, sepanjang tahun 2025 kita disuguhi kekerasan kepada media termasuk jurnalis yang masif.
Misalnya, teror kepada jurnalis Tempo, pencabutan kartu liputan istana pada jurnalis CNN serta gugatan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Tempo.
Di tengah peristiwa banjir Sumatra lalu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya meminta media memberitakan hal yang positif dan menghindari untuk menyampaikan kekurangan pemerintah.
Teddy menyebut bahwa media sebaiknya tidak menggiring opini seolah-oleh pemerintah tidak bekerja. Sebelumnya Reporters Without Borders (RSF) menyampaikan kutukan keras terhadap serangan pada 16 jurnalis yang tengah melakukan liputan demontrasi pada medio 25 Agustus 2025.
Secara umum, RSF juga mengumumkan indeks kebebasan pers di Indonesia pada rangking 127 dari 180 negara (turun dibandingkan tahun 2024 yang berada di peringkat 111).
Indikator yang digunakan oleh RSF meliputi legal framework, economic context, sociocultural context, safety. Sebagai gambaran, Malaysia berada di peringkat 88 sedangkan Thailand pada peringkat 85.
Alhasil, kelindan intervensi negara pada aktivitas jurnalistik semakin meminggirkan kepentingan publik.
Belum lagi kebijakan penguasa tersebut difasilitasi oleh bisnis media dan regulasi yang tidak memungkinkan adanya partisipasi masyarakat luas.
Akhirnya, semakin banyak ‘ruang gelap’ yang luput dari perhatian padahal di dalamnya ada kebijakan yang berkaitan dengan warga negara sedang diputuskan.
Jika berkaca pada gambaran di atas maka kita memang tengah berada dalam upaya pelemahan nalar publik yang serius serta masif.
Upaya sistemik dijalankan untuk menggiring kita pada situasi serba tertutup dan ketakutan, lalu ketidakbenaran menjadi sesuatu yang wajar dan normal.
Opini ditulis oleh Senja Yustitia
Peminat kajian jurnalisme
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta








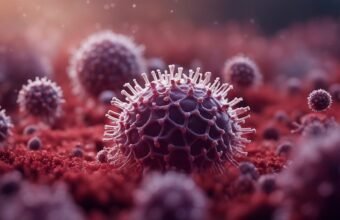


No Comment! Be the first one.