Kasus bunuh diri anak di NTT bukti kemiskinan ekstrem yang diabaikan negara
Kasus bunuh diri anak di NTT merupakan bentuk ekspresi kebuntuan korban akibat hilangnya harapan terhadap masa depan. Tindakan tersebut mencerminkan tekanan sosial yang berat.

Kasus bunuh diri anak sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (4/2/2026) lalu yang dipicu ketidakmampuan keluarga memenuhi kebutuhan sekolah, seperti alat tulis, menjadi potret kelam kemiskinan ekstrem yang luput dari perhatian negara.
Table Of Content
Diberitakan di berbagai media, korban meminta buku tulis kepada ibunya yang merupakan ibu tunggal. Akan tetapi, sang ibu mengakui tidak memiliki biaya untuk membelikan buku tulis itu.
Apalagi, ayah korban, meninggalkan ia dan ibunya sejak korban berada dalam kandungan dan ibu harus menafkahi lima anak seorang diri.
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ane Permatasari menilai, peristiwa itu menunjukkan lemahnya sistem perlindungan sosial negara.
Keberadaan program bantuan sosial belum otomatis menjamin perlindungan nyata bagi kelompok paling rentan. Lemahnya pendataan, tidak optimalnya deteksi dini lintas sektor, serta pendekatan kebijakan yang masih administratif dan reaktif membuat kemiskinan ekstrem kerap tidak teridentifikasi.
“Ini bukan sekadar persoalan satu keluarga miskin yang tidak menerima bantuan. Ini adalah kegagalan struktural negara dalam melindungi warga yang paling rentan, khususnya anak. Ketika kebutuhan paling dasar seperti alat tulis sekolah tidak terpenuhi dan tidak ada satu pun institusi yang merespons, maka negara sejatinya berhenti hadir sebelum menyentuh realitas kehidupan warganya,” ujar Ane, Jumat (6/2/2026).
Menurutnya, sistem kebijakan sosial kerap gagal mengenali kemiskinan pada lapisan paling bawah.
Keluarga miskin ekstrem sering kali tidak tersentuh bantuan bukan karena ketiadaan kebijakan, melainkan akibat desain dan tata kelola kebijakan yang belum cukup adaptif dan inklusif.
Ane mengungkap, implementasi kebijakan negara dituntut aktif dan peka terhadap kondisi lapangan.
“Pendataan adalah persoalan teknis, tetapi implementasi adalah persoalan etis dan institusional. Kebijakan publik tidak boleh dijalankan semata sebagai prosedur administratif. Jika tanda-tanda kerentanan sudah sangat kasatmata, intervensi seharusnya tetap dilakukan meskipun nama keluarga tersebut tidak tercantum dalam basis data,” tegasnya.
Tidak adanya intervensi dari sekolah, perangkat desa, maupun layanan sosial terdekat, lanjut Ane, mencerminkan lemahnya tata kelola kolaboratif antaraktor.
Padahal, sekolah dan guru merupakan pihak yang berada di garis terdepan dan paling dekat dengan kehidupan anak.
“Sekolah, puskesmas, dan desa seharusnya menjadi sistem peringatan dini. Ketika ada anak yang mulai menunjukkan tanda-tanda kesulitan ekstrem, baik secara ekonomi maupun psikososial, kondisi itu harus segera memicu respons lintas sektor,” jelasnya.
Paradigma bantuan sosial masih reaktif
Tak hanya itu, Ane juga mengkritik paradigma bantuan sosial yang masih bersifat reaktif, yakni baru bekerja setelah warga jatuh miskin atau tercatat dalam sistem. Pendekatan ini, menurutnya, membuat kebijakan sosial kehilangan fungsi pencegahan.
“Bantuan sosial kita masih menunggu warga jatuh terlalu dalam baru kemudian hadir. Ini menunjukkan paradigma yang keliru. Negara seharusnya bekerja secara preventif, berbasis risiko, serta memanfaatkan sekolah, puskesmas, dan desa sebagai sistem peringatan dini,” jelasnya.
Tragedi di NTT ini, kata Ane, harus menjadi peringatan keras bagi negara dan pemerintah daerah. Selama kebijakan sosial masih dipahami sebagai bantuan karitatif, bukan sebagai hak warga negara, kegagalan serupa berpotensi terus berulang.
“Ketika seorang anak kehilangan nyawa akibat kemiskinan yang tidak terdeteksi, itu bukan kegagalan individu. Itu adalah kegagalan negara, bukan hanya gagal mencatat, tetapi juga gagal bertindak,” pungkasnya
Pemerintah daerah jadi garda terdepan
Ane menjelaskan lebih jauh, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai aktor terdepan dalam mendeteksi dan merespons kemiskinan ekstrem.
“Idealnya, pemerintah daerah berperan sebagai frontline guardian. Artinya, pemda tidak hanya menunggu data atau usulan bantuan, tetapi aktif memastikan tidak ada anak dan keluarga yang jatuh terlalu dalam tanpa terdeteksi,” terangnya.
Dalam situasi darurat sosial, lanjut Ane, pemerintah daerah perlu memiliki ruang untuk melakukan intervensi cepat tanpa terhambat prosedur administratif yang panjang. Pendekatan ini dinilai krusial agar bantuan dapat hadir sebelum kondisi warga semakin memburuk.
“Kebijakan publik tidak bisa sepenuhnya bergantung pada data yang sempurna. Pemda perlu berani menggunakan diskresi untuk intervensi cepat, terutama ketika menyangkut keselamatan dan masa depan anak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ane menilai bahwa evaluasi kebijakan bantuan sosial juga perlu diubah. Selama ini, keberhasilan sering kali diukur dari besarnya penyaluran bantuan atau tingkat serapan anggaran. Padahal, indikator tersebut belum tentu mencerminkan dampak nyata di lapangan.
Ia mendorong agar indikator keberhasilan kebijakan sosial mencakup penurunan angka putus sekolah, berkurangnya keluarga miskin ekstrem yang terlewat dari bantuan, kecepatan respons sejak tanda kerentanan terdeteksi hingga intervensi dilakukan, serta kuatnya integrasi antara bantuan sosial dengan layanan pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, penguatan deteksi dini dan koordinasi lintas sektor bukan sekadar persoalan teknis, melainkan perubahan paradigma. Bantuan sosial harus dipahami sebagai hak warga negara yang dijamin negara, bukan sebagai pemberian karitatif yang menunggu permohonan.
Masalah yang berakar dari ketimpangan struktural
Tidak berbeda jauh dengan Ane, sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta atau yang akrab disapa Ab, menilai peristiwa tersebut tidak dapat dilihat sebagai persoalan individu semata, melainkan sebagai tanda kegagalan struktural negara dalam melindungi anak-anak.
Menurut Ab, kasus bunuh diri anak dan remaja menunjukkan adanya persoalan sosial yang kompleks dan berakar pada ketimpangan struktural.
Ia menegaskan, kasus tersebut merupakan puncak akumulasi tekanan sosial akibat kegagalan negara dalam menyediakan layanan dasar yang merata.
“Fenomena ini harus dilihat sebagai problem sosial yang bersifat struktural. Ketimpangan ekonomi yang semakin lebar menyebabkan sebagian masyarakat hidup dalam kondisi ekstrem, bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan paling mendasar”, ujarnya, Kamis (5/2).
Ia menjelaskan, kekerasan struktural negara tampak dalam praktik pembangunan yang dinilai lebih menguntungkan kelompok elit, sementara masyarakat miskin mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
“Kondisi tersebut, menurutnya, menciptakan keputusasaan yang meresap ke dalam dunia batin anak,” jelasnya.
Kasus bunuh diri ekspresi kebuntuan anak
Ab menilai kasus bunuh diri anak merupakan bentuk ekspresi kebuntuan akibat hilangnya harapan terhadap masa depan.
Ia menekankan bahwa anak-anak belum memiliki kemandirian penuh untuk mengambil keputusan eksistensial, sehingga tindakan tersebut mencerminkan tekanan sosial yang berat.
“Pilihan bunuh diri menjadi bahasa kegelapan ketika anak tidak memiliki ruang untuk mengekspresikan perasaan, kecemasan, dan harapannya. Ini menunjukkan hilangnya ekspektasi terhadap masa depan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ab menyoroti peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai bagian dari tiga pusat pendidikan yang dinilai belum menyediakan ruang dialogis bagi anak.
Ia menilai relasi kekuasaan yang cenderung otoriter membuat anak tidak memiliki ruang aman untuk menyampaikan perasaan dan pemikirannya.
“Di keluarga sering tidak ada afeksi, di masyarakat tidak ada pengakuan terhadap hak anak, dan di sekolah guru masih diposisikan sebagai pusat kebenaran. Anak akhirnya tidak memiliki ruang untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan”, ungkapnya.
Ab menegaskan bahwa negara dinilai abai dalam melindungi anak, terutama ketika di satu sisi menuntut kedisiplinan dan prestasi pendidikan, namun disisi lain gagal memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
“Negara terlalu banyak menuntut anak untuk menjadi generasi unggul, tetapi tidak mampu menyediakan fasilitas dasar untuk hidup layak. Ini merupakan ironi,” tegasnya.
Perubahan mendasar dalam tata kelola negara serta penguatan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat diperlukan sebagai upaya pencegahan.
Ia menekankan pentingnya menciptakan ruang afeksi di keluarga, menghapus stigma terhadap anak di masyarakat, serta menjadikan sekolah sebagai ruang dialog yang sehat dan inklusif.
Selain itu, Ab menekankan pentingnya kebijakan penanggulangan kemiskinan yang akurat dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme agar layanan sosial dapat tepat sasaran.
“Kepiluan anak-anak adalah kepiluan bangsa. Fenomena bunuh diri anak menunjukkan retaknya wajah Indonesia dan menjadi peringatan bahwa negara harus segera berbenah dalam melindungi generasi mudanya,” pungkasnya.









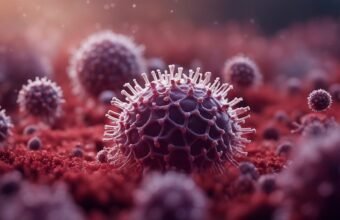

No Comment! Be the first one.