Psikolog UMY soroti ‘child grooming’ sebagai kekerasan emosional anak
Child grooming merupakan manipulasi emosional yang dibungkus keramahan dan dapat menimbulkan trauma jangka panjang pada anak.

Psikolog Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyoroti praktik child grooming sebagai bentuk kekerasan emosional terhadap anak yang kerap luput dari perhatian.
Pendekatan yang digunakan pelaku umumnya tidak bersifat mengancam, melainkan dibungkus melalui keramahan, perhatian, dan kedekatan yang terasa aman sesuatu yang mudah diterima, bahkan dirindukan, oleh anak.
Psikolog UMY, Cahyo Setiadi Ramadhan, menjelaskan bahwa child grooming merupakan pola manipulasi emosional yang dilakukan orang dewasa untuk membangun relasi dengan anak secara bertahap. Proses ini berlangsung tanpa paksaan dan sulit dikenali sejak awal, hingga pada akhirnya menjerat korban dalam ketergantungan emosional yang berisiko.
“Child grooming dilakukan melalui proses yang perlahan dan manipulatif. Pelaku berupaya menciptakan ketergantungan emosional pada anak. Ketika anak sudah merasa aman dan bergantung, di situlah pelaku mulai mengambil keuntungan dari relasi tersebut, yang paling sering berujung pada eksploitasi seksual,” ujar Cahyo saat ditemui di UMY, Sabtu (17/1/2025).
Gambaran tentang bagaimana child grooming bekerja dapat dilihat dari kasus yang belakangan mencuat dan dialami aktris Aurelie Moeremans sejak usia remaja.
Relasi yang pada awalnya tampak aman dan penuh dukungan perlahan berubah menjadi ruang yang menyimpan ketimpangan kuasa dan kerentanan.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa child grooming bukan peristiwa yang berdiri sendiri.
Praktik ini kerap berlangsung di ruang-ruang yang dianggap aman, seperti rumah, lingkungan pertemanan, atau relasi dekat yang telah lama terbangun.
Ketimpangan usia, pengalaman hidup, hingga otoritas sosial membuat anak berada dalam posisi yang sulit untuk menolak atau mempertanyakan relasi yang dijalaninya.
Dalam banyak situasi, anak dibiasakan untuk patuh dan percaya pada orang dewasa, bahkan ketika muncul rasa tidak nyaman yang belum mampu diberi nama. Kondisi ini semakin mempersulit anak untuk mengenali bahwa relasi yang dijalani menyimpan unsur manipulasi.
Menurut Cahyo, salah satu faktor yang membuat child grooming kerap luput dari perhatian adalah cara pelaku menampilkan diri.
Pelaku tidak hadir sebagai ancaman, melainkan sebagai figur dewasa yang peduli, suportif, dan bisa dipercaya. Dalam situasi seperti ini, lingkungan sekitar pun sering kali ikut lengah.
“Pelaku biasanya ramah, perhatian, mau mendengarkan keluh kesah anak, dan memberikan validasi emosional. Dari luar, pelaku tampak seperti orang dewasa yang baik. Padahal, di balik sikap itu terdapat motif yang tidak sehat dan berpotensi merusak perkembangan psikologis anak,” ungkapnya.
Akibatnya, child grooming kerap terlambat disadari, baik oleh korban maupun orang-orang terdekat. Anak sering kali belum memiliki bahasa untuk menjelaskan ketidaknyamanan yang dirasakan, sementara perhatian dari orang dewasa justru dianggap sebagai bentuk kepedulian.
Di sisi lain, lingkungan cenderung menormalisasi relasi yang tampak dekat dengan dalih dukungan emosional atau bimbingan.
Dampak dari child grooming tidak berhenti pada momen relasi itu berlangsung. Cahyo menyebut korban berisiko mengalami luka psikologis yang menetap dan memengaruhi kehidupan hingga dewasa.
Pada tahap awal, anak sering mengalami kebingungan emosional, rasa tidak nyaman, dan konflik batin. Perasaan tersebut kerap tidak dipahami sebagai bentuk kekerasan, sehingga dibiarkan mengendap dan berkembang menjadi trauma.
“Dalam jangka panjang, korban dapat mengalami penurunan kepercayaan diri, kecemasan berlebih, kesulitan membangun relasi yang sehat, hingga gangguan stres pascatrauma atau PTSD. Rasa bersalah karena merasa tidak mampu menolak atau melawan sering kali terbawa hingga korban dewasa,” jelasnya.
Luka akibat child grooming tidak selalu muncul dalam bentuk yang kasat mata.
Banyak korban baru menyadari pengalaman yang dialaminya setelah memasuki usia dewasa, ketika pola relasi yang tidak sehat terus berulang atau rasa bersalah tak kunjung mereda.
Trauma semacam ini kerap dipahami sebagai persoalan personal, padahal berakar pada relasi timpang yang terbentuk sejak anak berada dalam posisi rentan.
Di titik inilah, menurut Cahyo, pencegahan menjadi tanggung jawab bersama, bukan semata beban korban. Upaya pencegahan tidak bisa dilepaskan dari peran orang tua dan lingkungan terdekat.
“Anak perlu dibekali pemahaman tentang batasan diri, bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh, serta keberanian untuk mengatakan tidak. Dengan pendampingan emosional yang kuat, orang dengan niat tidak baik akan jauh lebih sulit memasuki dunia anak,” pungkasnya.








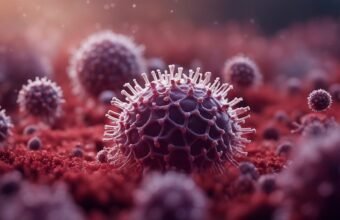


No Comment! Be the first one.